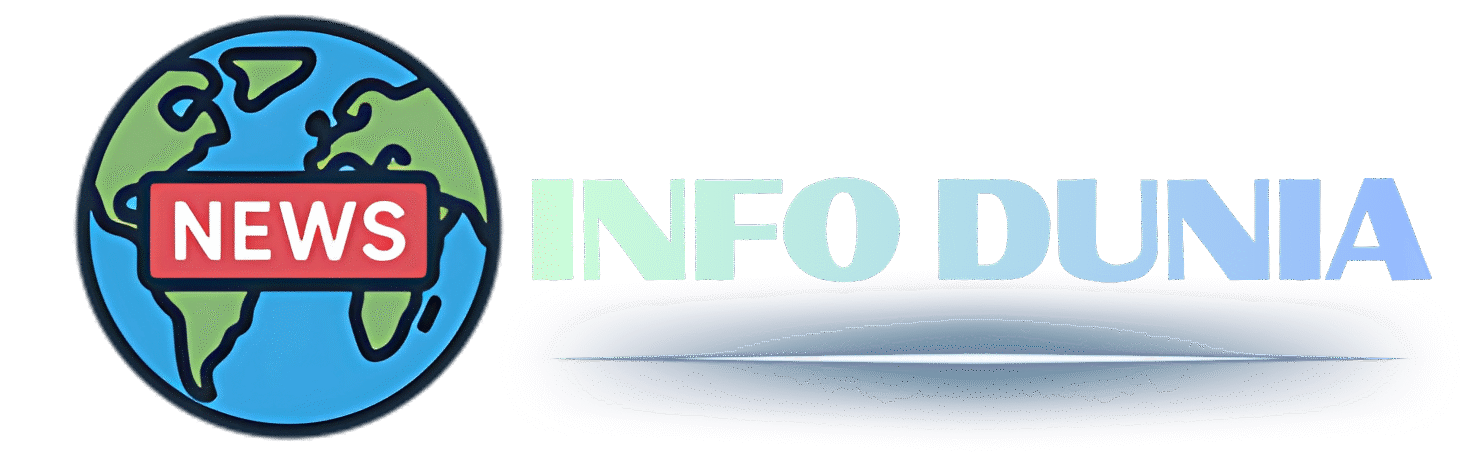“Polisi jadi pembunuh.” Kalimat ini mungkin terdengar menyakitkan bagi telinga para penjaga hukum, namun bagi warga di Jalan RSUD Maren Hi Noho Renuat, Desa Fiditan, Kota Tual, kata-kata tersebut adalah cerminan realitas yang sangat pahit. Pada Kamis pagi, 19 Februari 2026, sebuah insiden maut menghancurkan harapan sebuah keluarga dan memicu kemarahan publik di Maluku.
Seorang oknum Brimob, Bripda Masias Siahaya (MS), diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan tewasnya seorang remaja di bawah umur dan luka berat pada kakaknya. Kejadian ini bukan hanya masalah “oknum”, melainkan potret kegagalan sistemik dalam mendidik aparat yang seharusnya menjadi pelindung, bukan penindas.

Kronologi Kekejaman di Jalanan
Arianto Tawakal, seorang remaja berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku MTsN 1 Maluku Tenggara, harus merenggang nyawa dengan cara yang tragis. Ia tewas setelah kepalanya dipukul menggunakan helm oleh Bripda MS hingga terjatuh dari sepeda motor. Kakaknya, Nasri Karim (15), siswa MAN Maluku Tenggara, menderita patah tulang tangan yang serius dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ironisnya, tudingan awal yang sempat beredar menyebutkan bahwa kedua remaja ini terlibat dalam balap liar. Namun, fakta lapangan berbicara lain. Mereka baru saja pulang menunaikan ibadah shalat subuh—sebuah rutinitas religius yang suci yang berakhir menjadi mimpi buruk akibat arogansi aparat.
Baca Juga:
Janji Tegas dan Bayang-Bayang Impunitas
Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, bergerak cepat dengan menjanjikan penanganan tegas. Proses pidana kini tengah berjalan di Polres Tual, sementara sidang etik ditangani oleh Bidpropam Polda Maluku. Mabes Polri pun telah melayangkan permohonan maaf resmi dan menerjunkan Dansat Brimob untuk mendinginkan suasana di lapangan.
Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: Apakah permintaan maaf dan sidang etik cukup untuk menebus nyawa yang hilang?
Ancaman hukuman 15 tahun penjara berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP memang telah disiapkan bagi tersangka. Akan tetapi, publik sudah terlalu sering mendengar janji “transparansi” yang berakhir dengan sanksi administratif belaka. Tanpa proses pidana yang setimpal dan terbuka, keadilan bagi keluarga Arianto hanyalah bayang-bayang di atas kertas.
Penyakit Sistemik: Menakar Angka Kekerasan Polri
Jika kita melihat data secara jernih, insiden di Tual bukanlah kasus tunggal yang terisolasi. Ini adalah puncak gunung es dari masalah struktural yang kronis. Berdasarkan catatan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), selama periode 2020 hingga 2025, tercatat setidaknya ada 3.197 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian.
Artinya, rata-rata terjadi lebih dari 600 kasus kekerasan setiap tahunnya. Konsistensi angka ini membuktikan bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari budaya organisasi yang gagal dipangkas. Kurangnya akuntabilitas menjadi penghambat utama; personel yang terlibat sering kali hanya dijatuhi hukuman demosi atau pemecatan tanpa pernah menginjakkan kaki di balik jeruji besi penjara umum.
Kesan adanya impunitas—kekebalan hukum bagi pemegang senjata—semakin menguat di mata masyarakat. Kita tentu belum lupa pada tragedi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus 2025 lalu. Dalam kasus-kasus fatal seperti ini, ketimpangan antara aturan hukum formal dan sanksi internal sangat mencolok.
Urgensi Reformasi Total
Mengapa seragam yang dibayar oleh pajak rakyat justru digunakan untuk menindas rakyat? Reformasi kepolisian tidak boleh lagi hanya bersifat kosmetik atau sekadar mengganti slogan. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap:
- Sistem Rekrutmen dan Pendidikan: Memastikan kesehatan mental dan kontrol emosi aparat berada di atas standar sebelum mereka diberi kewenangan membawa senjata atau alat pemukul.
- Transparansi Proses Hukum: Penanganan kasus pidana oleh anggota Polri harus bisa diakses publik perkembangannya, bukan hanya diselesaikan di balik pintu sidang etik tertutup.
- Pengawasan Eksternal yang Kuat: Memperkuat peran Kompolnas dan lembaga independen lainnya agar tidak menjadi sekadar “stempel” bagi kebijakan Polri.
Kesimpulan: Menanti Keadilan di Maluku
Tragedi Tual adalah ujian bagi kepemimpinan Polri di tahun 2026. Jika Bripda MS hanya berakhir dengan sanksi etik tanpa hukuman pidana maksimal, maka luka masyarakat Maluku—dan Indonesia—akan semakin menganga. Penegakan hukum yang adil adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa janji “melindungi dan melayani” bukan sekadar omong kosong yang ditulis di dinding kantor polisi.
Darah Arianto Tawakal menuntut pertanggungjawaban. Jangan sampai laras senjata negara kembali menyalak ke arah mereka yang baru saja pulang bersujud di hadapan Tuhan.